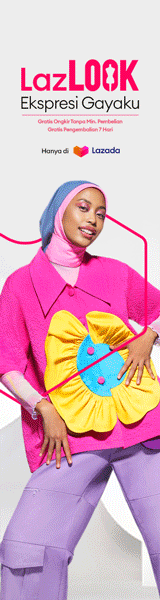Oleh: Rahmadina Komisariat FKIP HMI Cabang Palu
dteksinews, Palu-Sebagai bagian dari Gen Z, saya tumbuh di era yang katanya paling terbuka. Media sosial memberi ruang luas untuk berbicara, berpendapat, dan menyuarakan keresahan. Perempuan Gen Z terlihat lebih berani: berani bicara soal kesehatan mental, relasi tidak sehat, body image, hingga ketidakadilan yang dialami sehari-hari. Namun di balik semua itu, satu pertanyaan terus muncul “mengapa ketika perempuan bersuara, masih saja ada yang meminta untuk diam”?
Fenomena ini terasa nyata di media sosial. Ketika perempuan Gen Z membagikan pengalaman atau pendapat, respons yang muncul sering kali bukan empati, melainkan penghakiman. Perempuan dianggap terlalu sensitif, berlebihan, atau mencari validasi. Suara perempuan seolah sah hanya jika disampaikan dengan nada lembut dan tidak mengganggu kenyamanan siapa pun. Begitu suara itu tegas, kritis, atau menyentuh isu sensitif, penolakan pun datang.
Menurut saya, persoalan utamanya bukan pada keberanian perempuan Gen Z untuk bersuara, melainkan pada budaya yang belum siap menerima suara itu. Masyarakat masih terbiasa melihat perempuan sebagai pihak yang seharusnya mengalah, memahami, dan menjaga suasana tetap “tenang.” Akibatnya, perempuan yang vokal sering dianggap melawan norma, padahal yang dilakukan hanyalah menyampaikan kebenaran dari pengalaman sendiri.
Ironisnya, pembungkaman ini tidak jarang datang dari sesama Gen Z. Di satu sisi, Gen Z dikenal kritis dan sadar isu sosial. Namun di sisi lain, masih ada kecenderungan untuk meremehkan suara perempuan, terutama ketika pengalaman tersebut dianggap tidak sesuai dengan realitas pribadi orang lain. Kalimat seperti “nggak semua laki-laki begitu” atau “kok dibesar-besarkan” menjadi cara halus untuk meniadakan pengalaman perempuan.
Pengalaman perempuan sering dipaksa untuk selalu rasional dan rapi agar dianggap valid. Padahal, tidak semua luka bisa dijelaskan dengan data atau bahasa akademik. Ada emosi, ketakutan, dan kelelahan yang menyertainya. Ketika perempuan Gen Z memilih untuk jujur dan terbuka, respons yang seharusnya muncul adalah mendengarkan, bukan menyuruh diam.
Saya percaya, bersuara bukan berarti ingin menang atau merasa paling benar. Bagi banyak perempuan, bersuara adalah bentuk bertahan. Bertahan agar pengalaman tidak terulang pada orang lain. Bertahan agar luka tidak terus dianggap sepele. Diam mungkin terlihat aman, tetapi diam terlalu lama justru membuat ketidakadilan terasa normal.
Gen Z sering disebut sebagai generasi perubahan. Namun perubahan tidak akan terjadi jika suara perempuan masih dipilih-pilih untuk didengar. Tidak semua suara harus nyaman. Ada suara yang memang hadir untuk mengguncang, menyadarkan, dan memaksa kita berpikir ulang tentang apa yang selama ini dianggap wajar.
Pada akhirnya, perempuan Gen Z tidak membutuhkan panggung untuk tampil sempurna. Yang dibutuhkan adalah ruang untuk berbicara tanpa takut diremehkan. Jika hari ini perempuan masih disuruh diam, maka yang perlu dipertanyakan bukan keberanian perempuan, melainkan sejauh mana masyarakat termasuk Gen Z sendiri benar-benar siap menerima kejujuran.
Perempuan akan terus bersuara. Bukan karena ingin melawan, tetapi karena diam bukan lagi pilihan.(*)